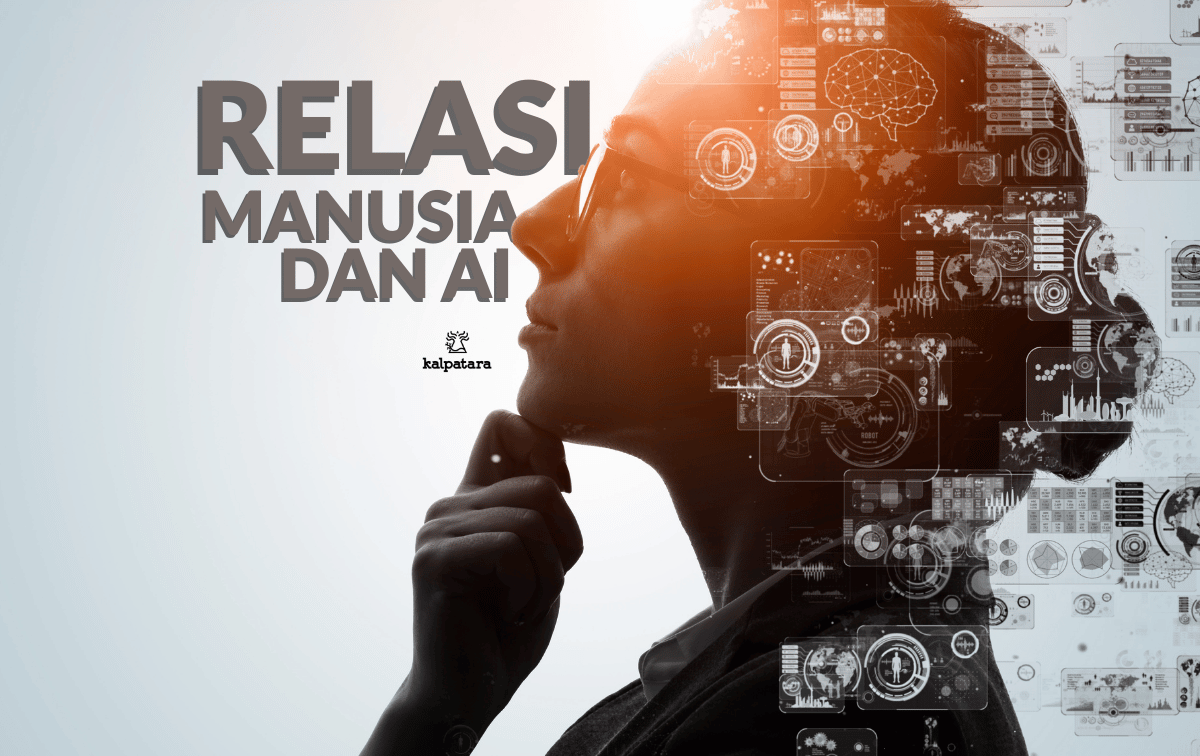AI dan Relasi Kuasa
Pembicaraan tentang kecerdasan buatan sering kali diasumsikan bersifat universal. Seakan-akan teknologi ini bekerja dengan cara yang sama di mana pun ia diterapkan. AI dipresentasikan sebagai kemajuan netral yang dapat diadopsi secara merata, tanpa perlu banyak penyesuaian terhadap konteks sosial, politik, atau historis. Namun asumsi inilah yang justru perlu dipertanyakan, terutama ketika AI dihadirkan dalam ruang-ruang yang memiliki sejarah kolonial dan ketimpangan struktural yang panjang.
Perspektif dekolonisasi menjadi penting karena ia mengingatkan bahwa teknologi tidak pernah hadir dalam ruang kosong. Cara sebuah teknologi dirancang, dilatih, dan diterapkan selalu membawa jejak nilai, kepentingan, dan relasi kuasa tertentu. Dalam konteks AI, relasi ini tampak jelas pada kenyataan bahwa sebagian besar sistem dikembangkan di pusat-pusat teknologi Global North, dengan data, bahasa, dan asumsi yang lahir dari pengalaman sosial yang sangat spesifik.
Imperialisme telah menjadi faktor berpengaruh dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI), membentuk narasi, aplikasi, dan implikasi globalnya—Jian Carlos de Melo, “Decolonial AI: A Perspective on the Imperialist States’ Colonizing Quest for Labor Applied in the Development of Artificial Intelligence,” Brazilian Journal of Political Economy 45, no. 3 (2025)
Tanpa lensa dekolonisasi, adopsi AI di Global South berisiko mengulang pola lama. Teknologi diposisikan sebagai solusi eksternal yang harus diterima, bukan sebagai praktik yang dapat dinegosiasikan atau dibentuk ulang dari pengalaman lokal. Di sinilah pemikiran Heidegger tentang Enframing menjadi relevan. Teknologi tidak hanya menyediakan alat, tetapi juga membingkai cara dunia dipahami. Ketika pembingkaian ini datang dari luar, ia cenderung menyeragamkan pengalaman dan mengaburkan perbedaan konteks.
Membaca AI melalui perspektif dekolonisasi berarti membuka ruang kritis untuk bertanya bukan hanya tentang apa yang dapat dilakukan teknologi, tetapi tentang cara teknologi itu membentuk relasi sosial, kerja, dan pengetahuan. Pertanyaan tentang efisiensi, misalnya, tidak lagi diterima sebagai nilai netral, melainkan dapat ditelusuri dengan pertanyaan: efisiensi bagi siapa, dengan biaya apa, dan siapa yang menentukan ukurannya?
Dengan kerangka ini, pembahasan tentang AI di Global South tidak dimulai dari kekaguman terhadap kemampuan teknisnya, tetapi dari kesadaran akan posisi dan pengalaman yang tidak setara dalam ekosistem teknologi global. Dari titik inilah kita dapat memahami AI bukan sekadar sebagai inovasi, melainkan sebagai fenomena politik dan kultural yang menuntut pembacaan yang lebih berhati-hati.
Pemikiran dekolonisasi membawa kita pada hadirnya reduksi pengalaman. Ketika AI digunakan untuk memetakan kemiskinan misalnya, mengelola bantuan sosial, atau menilai kelayakan kredit, manusia di Global South sering kali hadir di dalam sistem sebagai objek pengukuran, bukan subjek yang menentukan arah.
Di sinilah Gestell bisa dipahami. Kehidupan yang kompleks, relasi komunitas, ekonomi informal, solidaritas lokal diperas menjadi indikator dan skor. Apa yang tidak dapat diukur dengan mudah berisiko dianggap tidak ada.
Heidegger mungkin tidak pernah membayangkan AI, tetapi peringatannya terasa sangat relevan: bahaya teknologi bukan karena ia gagal memahami dunia, tetapi karena ia terlalu berhasil membingkai dunia dalam satu cara saja.
MIT Technology Review menyinggung bahwa masa depan AI akan ditentukan oleh siapa yang menguasai infrastruktur berupa data, komputasi, dan model dasar. Dalam konteks Global South, ini memunculkan pertanyaan politis yang tidak bisa dihindari: siapa yang menentukan bagaimana AI bekerja, dan untuk kepentingan siapa?
Jika negara-negara berkembang hanya menjadi pengguna akhir, maka AI berisiko memperkuat ketimpangan lama dalam bentuk baru. Bukan lagi kolonialisme teritorial, tetapi kolonialisme digital, di mana data lokal diekstraksi, diproses di tempat lain, lalu hasilnya dijual kembali sebagai layanan.
Dalam pembingkaian ini, Global South bukan ruang untuk berinovasi, melainkan ladang data dan pasar.
Perspektif dekolonisasi membuka kesempatan bagi kita untuk melihat adopsi teknologi tidak lagi dipahami sebagai proses netral, melainkan sebagai peristiwa politik yang membentuk ulang siapa yang memiliki otoritas pengetahuan, siapa yang menentukan standar, dan siapa yang menanggung konsekuensi.